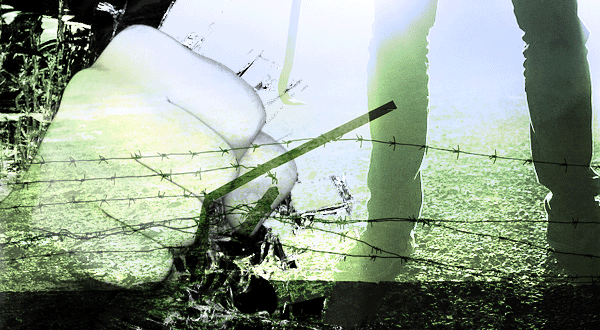Oleh: Vinsensius Sitepu
Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Even today we raise our hand against our brother… We have perfected our weapons, our conscience has fallen asleep, and we have sharpened our ideas to justify ourselves as if it were normal we continue to sow destruction, pain, death. Violence and war lead only to death (Paus Fransiskus, Vigil of Prayer for Peace, 2013)
Kekerasan sama tuanya dengan peradaban manusia. Selama itu pula manusia berusaha memahaminya semakin dalam dan mencari pemecahan atasnya. Semakin dalam kita ingin memahami, semakin masif pula jumlah kekerasan, terlebih-lebih jika menyangkut kepentingan harta. Teknologi komunikasi yang murah dan lintas wilayah, yang tidak digunakan bijak, kian menjadi akselerator kekerasan.
Kita pun menyadari bahwa manusia melebur dalam struktur sosialnya. Dengan demikian pula kita menyadari secara antropologis-historis manusia sejatinya adalah makhluk bebas dan plural, sekaligus maha kompleks. Makna kompleks dalam hal ini adalah, ketika kita merasa mendekati titik terang atas permasalahan, justru titik pangkalnya semakin menjauh. Membingungkan.
Perbedaan itu kasat mata, mulai dari dari sifat, cara berkomunikasi, tindakan, dan ekspresi. Terkadang pun perbedaan itu “dibeda-bedakan”, yang menghasilkan gesekan-gesekan sosial dan konflik horisontal. Dalam bahasa yang sangat logis, satu-satunya kesamaan manusia adalah perbedaan itu sendiri.
Dalam konteks kekerasan yang berindikasi pelanggaran HAM berat di Sari Rejo tempo hari, unjuk rasa warga terhadap aparat negara adalah dalam koridor ekspresi politik, organisasi tempatnya bernaung: negara. Maka, ketika warga menuntut yang dikatakan sebagai haknya, boleh kita sebut itu sebagai gagasan (wacana politik) warga di ruang publik nyata.
Politik Ruang Publik
Teori tindakan Hannah Arendt menegaskan, bahwa manusia dilihat dari tiga elemen utama, yaitu kerja, karya, dan tindakan. Dalam satu rumusan, Arendt mengemasnya sebagai bagian dari politik. Politik sendiri dapat dipandang sebagai suatu yang “dibuat”, bukan merupakan bawaan. Sementara itu “tindakan” adalah sebuah keniscayaan. Dari sini digarisbawahi: manusia dedefinisikan dari tindakannya, berbeda dengan kerja dan karya.
Mendekati teori itu dengan peristiwa terkini, tentara, dalam hal ini oknum prajurit TNI AU Lanud Soewondo, yang seenak perutnya melukai warga dan beberapa wartawan adalah kekerasan negara terhadap anggotanya sendiri. Seketika, negara terhitung gagal melindungi rakyatnya sendiri, tetapi memilih rakyat merasa takut dan berdarah. Di saat yang sama hukum tiada artinya di mata tentara. Ingat, negara sejatinya sebuah organisasi dengan rakyat sebagai anggotanya.
Kerja dan karya tentara yang sesungguhnya adalah pelindung dalam kondisi perang, sebuah “kekerasan yang resmi”, ketika negara sedang terancam dirongrong kekuasaan asing atau dihantam kekuatan dalam negeri yang ingin mendompleng kekuasaan.
Rakyat pengunjuk rasa bisa jadi keliru, tetapi hunusan rotan dan tendangan sepatu lars, rasanya tidak sepadan, terlebih-lebih menghalangai wartawan menjalankan tugasnya adalah pula pelanggaran hukum, pengangkangan konstitusi. Rakyat bukanlah sasaran panahan atau boneka latihan perang. Dan lagi, memohon maaf itu penting dan amat dihargai, tetapi itu teramat mudah dilakukan, ketika keselarasan sosial sudah diporak-porandakan. Logika dangkalnya demikian: pukul dulu, minta maaf kemudian. Tetapi logika terdalam adalah, siapa yang melanggar hukum, dan memang tentara harus taat hukum, harus mendapat ganjaran setimpal, atas nama hukum dan negara, ya termasuk warga, jikalau terbukti.
Banalitas Kekerasan
Tentara kita pahami didoktrin dan dididik melakukan “kekerasan” tetapi kekerasan yang terkendali, tidak ngasal, dan berasas hukum, terlebih-terlebih terikat ikrar Sapta Marga. Banalitas kekerasan dipahami sebagai situasi di mana kekerasan telah dianggap biasa, seolah-olah berada dalam konteks benar itu. Menyoal ini, Arendt mengungkapkan, bahwa kekerasan ataupun kejahatan muncul ketika hilangnya spontanitas manusia, yang didorong oleh tiga hal, yaitu ketumpulan hati nurani manusia, kegagalan berpikir kritis, dangkal dan banal dalam menilai serta menghakimi sesuatu. Dan yang paling penting, di atas semua itu, kekerasaan adalah puncak dari kegagalan dalam melakukan dialog dengan dirinya sendiri secara berkelanjutan dan telaten.
Kekerasan pun dapat didekati melalui perspektif totalitarianisme, tetapi secara parsial, yaitu kekerasan, propaganda dan konspirasi, serta teror. Dalam rangka mewujudkan itu secara efektif, maka negara menempuhnya melalui: represi, di mana militer sebagai eksekutor untuk teror dan intimidasi, preman untuk membuat kerusuhan, dan konflik SARA.
Membicarakan ideologi semacam itu, kita tentu ingat Soeharto, yang memberikan ruang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada militer, yang tidak hanya masuk ke ranah pertahanan dan keamanan, tetapi masuk ke relung-relung sosial dan privat warga Indonesia.
Kami menginginkan tentara yang baik hati, yang mampu mengendalikan emosinya. Kami menginginkan tentara yang tegas, tetapi tidak garang dan arogan dalam menyelesaikan masalah. Dan kami percaya, tentara secara institusi menghormati konstitusi dan hukum, serta menenerima konsekuensi atas peristiwa itu. Dengan sikap ksatria, jawablah: siap!